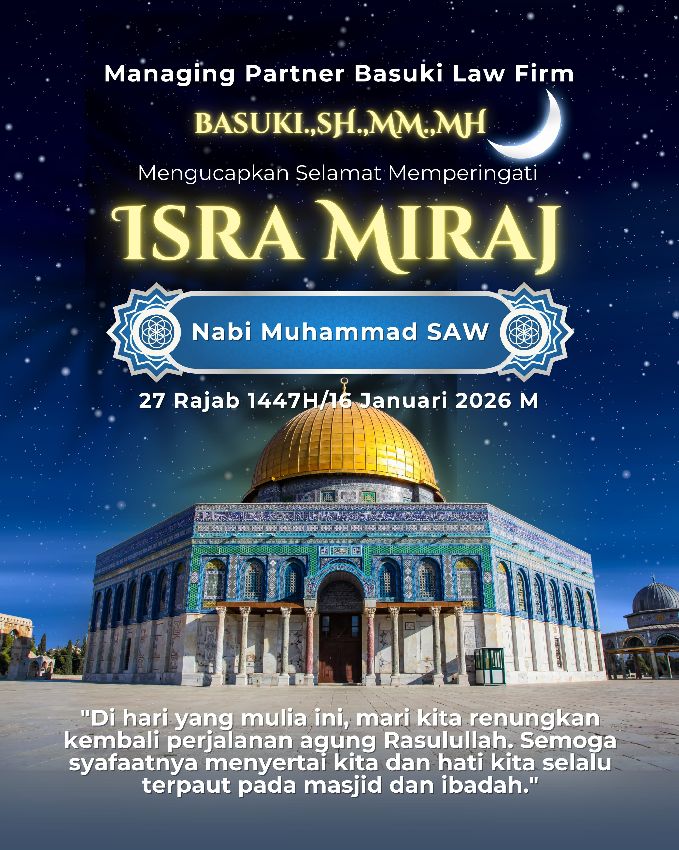TANGERANG SELATAN, (variabanten.com)-Wacana tentang kesetaraan gender di Indonesia telah menjadi pembahasan yang terus berkembang, terlebih sejak era reformasi yang membawa semangat perubahan. Namun kenyataannya, hukum yang seharusnya menjadi alat utama untuk menegakkan keadilan masih sering kali belum berpihak sepenuhnya kepada perempuan. Meskipun konstitusi dan berbagai undang-undang telah menjamin kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, implementasi di lapangan masih menyisakan banyak ketimpangan.
Salah satu penyebab utama dari ketimpangan ini adalah budaya patriarki yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Sistem nilai yang memposisikan laki-laki sebagai tokoh sentral dalam pengambilan keputusan sosial, politik, bahkan dalam keluarga, menyebabkan perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang diuntungkan. Ketika hukum dijalankan dalam konteks budaya yang bias gender, maka hasilnya pun sering kali merugikan perempuan — baik dalam hal perlindungan, keadilan, maupun partisipasi dalam ruang publik.
Penting untuk disadari bahwa diskriminasi gender terhadap perempuan bukan hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga terlembagakan secara sistemik, termasuk dalam formulasi kebijakan publik. Contoh nyata terlihat dalam polemik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Meskipun niatnya baik, beberapa pasal dalam RUU tersebut dinilai berpotensi justru memperkuat diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja. Ketentuan seperti cuti melahirkan yang terlalu panjang, misalnya, dikhawatirkan bisa membuat perusahaan enggan mempekerjakan atau mempromosikan karyawan perempuan karena dianggap sebagai beban biaya dan produktivitas.
Selain itu, kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik, masih marak terjadi meskipun sudah ada payung hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Banyak korban masih enggan melapor karena stigma sosial, minimnya perlindungan hukum yang nyata, dan proses hukum yang melelahkan serta tidak ramah perempuan. Hal ini menunjukkan adanya jurang besar antara hukum normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Padahal, payung hukum normatif Indonesia sudah cukup kuat. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tetapi kesetaraan itu belum sepenuhnya terwujud jika penegakan hukumnya masih mengabaikan realitas yang dihadapi perempuan.
Perlu digarisbawahi juga bahwa berbagai undang-undang lain seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memang sudah memberikan kerangka hukum yang cukup baik dalam melindungi hak perempuan. Namun demikian, kebijakan hukum yang baik tidak akan berdampak maksimal tanpa dukungan implementasi yang tegas, adil, dan berperspektif gender.
Sebagai contoh, dalam praktiknya, masih banyak perempuan yang kesulitan mengakses keadilan karena minimnya bantuan hukum, kurangnya petugas hukum yang memahami isu gender, serta sistem birokrasi yang lamban dan rumit. Selain itu, angka kekerasan seksual dan pernikahan anak masih tinggi di sejumlah daerah, yang memperlihatkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup tanpa pendekatan sosial dan kultural yang menyentuh akar masalah.
Padahal sudah jelas termuat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang dasar negaara yang mengatura tentang hal tersebut di antaranya yakni:
• UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): Menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 ayat (3): Menegaskan hak atas perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan jenis kelamin.
• UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: Menyediakan landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan, khususnya perempuan.
• UU No. 12 Tahun 2006 & UU No. 21 Tahun 2007: Melindungi hak kewarganegaraan dan korban perdagangan orang, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Namun beberapa pasal tersebut tidak cukup kuan untuk terciptanya keadilan gender.
Oleh karena itu secara normatif, Indonesia telah memiliki banyak peraturan yang mendukung kesetaraan dan perlindungan perempuan. Namun sayangnya, budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya perspektif gender dalam kebijakan publik, masih menjadi penghalang besar bagi terwujudnya keadilan gender yang sejati. Polemik dalam RUU KIA hanyalah satu dari banyak contoh bagaimana kebijakan bisa menjadi bumerang jika tidak dilandasi oleh pemahaman yang utuh terhadap isu perempuan.
Untuk membangun masyarakat yang benar-benar adil dan setara, diperlukan sinergi antara pembaruan hukum, pendidikan publik, dan transformasi budaya. Hukum harus menjadi alat pembebasan, bukan justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Perspektif gender harus ditanamkan dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan hukum. Selain itu, peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan juga sangat penting untuk membentuk kesadaran kritis dan budaya hukum yang lebih adil terhadap perempuan.
Kini saatnya hukum tidak hanya menjadi kumpulan pasal-pasal, tapi benar-benar hadir sebagai alat pembebasan. Upaya perbaikan harus dilakukan secara komprehensif: memperkuat hukum yang berpihak pada keadilan gender, melibatkan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan, dan memberantas budaya patriarki melalui pendidikan serta sosialisasi di semua lapisan masyarakat.
Jika kita ingin membangun Indonesia yang adil dan setara, maka hukum harus menjadi teman perempuan, bukan tembok penghalang bagi kesetaraan. Jangan biarkan hukum menjadi alat yang secara tidak sadar melanggengkan ketidakadilan.
VB-Putra Trisna.