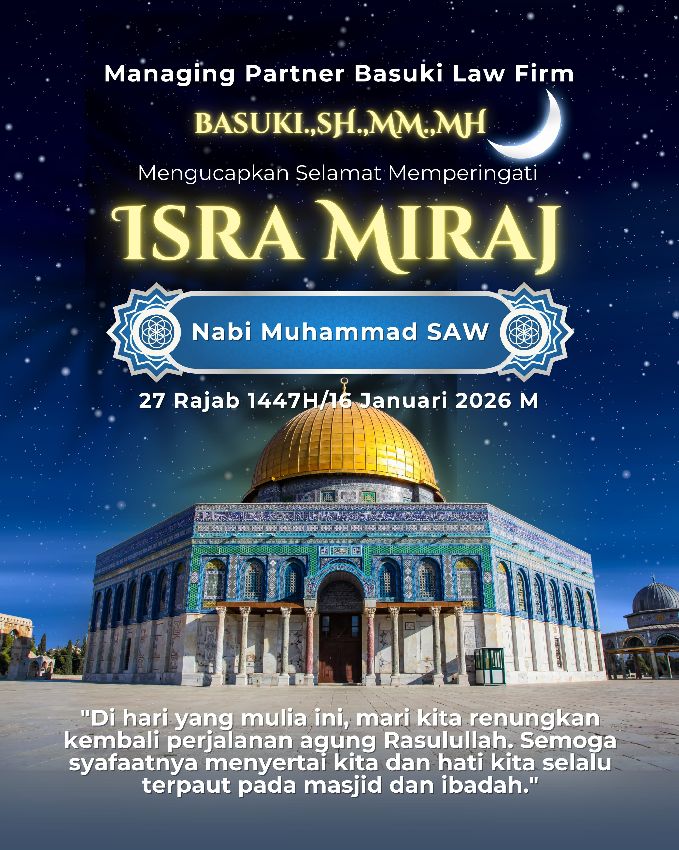TANGERANG SELATAN, (variabanten.com)-Pemilu adalah momen puncak dari sistem demokrasi, tempat rakyat diberi kuasa untuk memilih wakil yang akan membuat dan mengawasi hukum. Namun dalam praktiknya, setiap menjelang pemilihan umum, publik kerap dihadapkan pada kenyataan pahit: munculnya kembali nama-nama mantan narapidana korupsi dalam daftar calon legislatif.
Mereka datang dengan bendera hak politik yang telah “dipulihkan”, meskipun luka kepercayaan publik belum sembuh. Di sinilah konflik antara legalitas formal dan kepatutan moral mengemuka. Pertanyaannya: apakah mantan terpidana korupsi layak kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, meskipun hukum mengizinkannya?
Kerangka Konstitusional Hak Politik
Hak untuk dipilih dan memilih dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak konstitusional ini bukan hak absolut, melainkan hak yang tunduk pada pembatasan yang sah sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 4/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa pembatasan hak politik mantan narapidana dapat dibenarkan sepanjang:
• Ditentukan melalui undang-undang,
• Bersifat proporsional,
• Beralasan objektif dan tidak diskriminatif.
Artinya, dalam konteks mantan narapidana korupsi, negara memiliki landasan hukum dan konstitusional untuk memberlakukan pembatasan, terutama karena korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam sendi-sendi demokrasi.
Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)
Korupsi dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap keadilan sosial, pembangunan, dan kepercayaan publik terhadap negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moralitas kekuasaan.
Dalam pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bukan semata-mata deretan norma formal, melainkan alat perubahan sosial yang berpihak pada nilai keadilan substantif. Maka, ketika hukum positif masih membuka celah bagi mantan pelaku korupsi untuk mencalonkan diri, intervensi etik dan moral masyarakat menjadi mutlak diperlukan.
Dimensi Etika dan Integritas Politik
Secara etik, seorang mantan narapidana korupsi telah gagal menjaga integritas jabatan publik. Integritas merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan politik. Menurut teori virtue ethics (etika keutamaan) yang dipopulerkan oleh Aristoteles, jabatan publik menuntut bukan hanya kecakapan, tetapi juga karakter moral.
Jika pemilu adalah mekanisme demokratis untuk merekrut pemimpin yang mewakili aspirasi dan menjamin keadilan, maka memberi ruang kepada mantan koruptor adalah bentuk kompromi serius terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.
Dilema Legalitas dan Celah Legislasi
Saat ini, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang masih memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk maju dalam pemilu, dengan syarat:
1. Telah bebas selama lima tahun,
2. Mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya mantan napi,
3. Bukan residivis berulang.
Komisi Pemilihan Umum sempat berinisiatif membuat larangan eksplisit melalui PKPU No. 20 Tahun 2018, tetapi digugurkan Mahkamah Agung karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif kita belum secara tegas melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri, dan karenanya perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu secara komprehensif.
Perbandingan Internasional: Bagaimana Negara Lain Bersikap?
Beberapa negara telah menerapkan pembatasan ketat terhadap eks napi korupsi:
• Filipina: melalui Konstitusinya, melarang pejabat publik yang pernah dihukum karena kejahatan berat, termasuk korupsi, untuk kembali ke jabatan publik.
• Italia: memberlakukan Legge Severino yang melarang mantan pejabat publik yang divonis korupsi untuk mencalonkan diri selama 6 tahun setelah menjalani hukuman.
• India: Mahkamah Agung India melarang politisi yang dijatuhi hukuman dua tahun atau lebih untuk mencalonkan diri dalam pemilu.
Langkah-langkah ini diambil demi menjaga integritas kelembagaan negara dan mencegah masuknya kembali pelaku kejahatan berat ke dalam struktur kekuasaan.
Tanggung Jawab Partai Politik dan Publik
Sebelum hukum positif berubah, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk menyaring calon legislatif berdasarkan rekam jejak integritas, bukan sekadar elektabilitas. Menjadi fatal jika parpol justru menjadi kendaraan bagi mantan koruptor untuk mencuci reputasi politik.
Di sisi lain, masyarakat sipil dan media juga perlu memainkan peran kontrol sosial dan pendidikan publik, agar pemilih lebih kritis dan rasional dalam menentukan pilihan.
Penutup: Menjaga Demokrasi dari Dalam
Memulihkan hak politik seorang mantan narapidana korupsi memang dapat dibenarkan dalam konteks hak asasi manusia. Namun dalam sistem demokrasi yang sehat, hak itu tidak berdiri sendiri, melainkan harus ditimbang dengan kepentingan publik, moralitas politik, dan integritas kelembagaan.
Memberi ruang kepada mantan koruptor untuk kembali ke legislatif, berarti membiarkan kerusakan yang pernah terjadi terulang. Maka, negara dan masyarakat harus bersikap: tidak cukup sekadar legal, tapi harus juga bermoral.
Sebagaimana diingatkan oleh Gustav Radbruch dalam teori tiga nilai dasar hukum — keadilan, kepastian, dan kemanfaatan — hukum yang hanya berpihak pada kepastian formal, tapi mengabaikan keadilan dan moral publik, adalah hukum yang kehilangan maknanya.
VB-Putra Trisna.