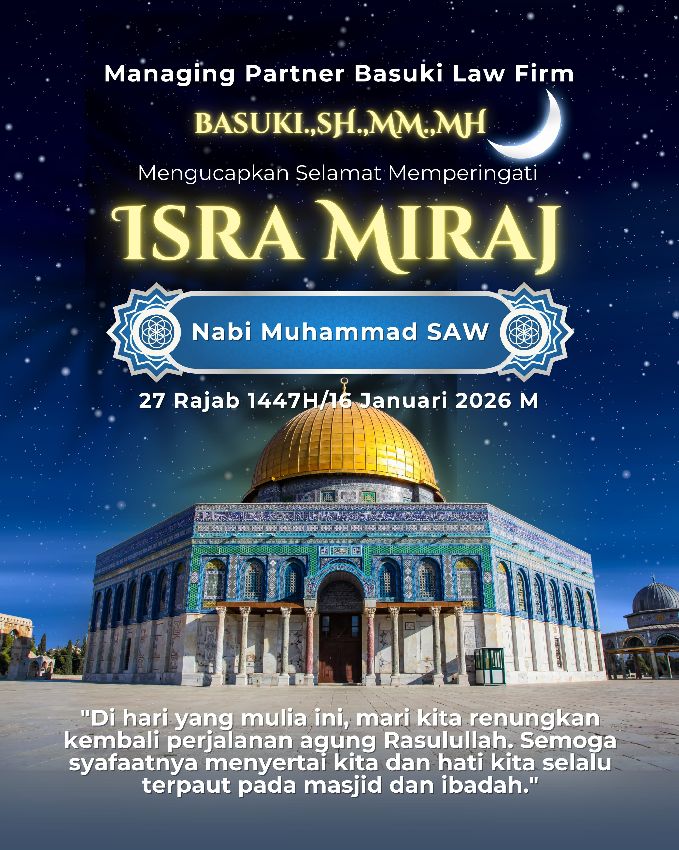TANGERANG SELATAN, (variabantwn.com)-Perkembangan teknologi dan media sosial memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Tapi di balik kemudahan tersebut, ada satu masalah serius yang semakin sering terjadi, yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (hate speech). Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tapi juga dapat memecah belah masyarakat dan mengancam persatuan bangsa.
Hoaks dan Ujaran Kebencian: Masalah yang Makin Meluas
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja, terdapat 1.923 konten hoaks yang tersebar di berbagai platform digital1. Selain itu, konten berisi ujaran kebencian juga semakin meningkat, terutama menjelang momen-momen politik seperti pemilu. Bahkan, Ketua KPU RI menyebut hoaks dan hate speech sebagai “narkotika digital” karena dampaknya bisa merusak cara berpikir dan emosi masyarakat.Yang lebih memprihatinkan, hoaks seringkali menyebar lebih cepat dibandingkan fakta. Banyak orang yang asal menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya, terutama di grup WhatsApp keluarga atau media sosial. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Menurut survei Katadata Insight Center, hanya sekitar 21% hingga 36% masyarakat yang mampu mengenali hoaks dengan baik2.
Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk menindak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, antara lain melalui:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 Ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang berita bohong dan ujaran kebencian berbasis SARA.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan hasutan.
3. Beberapa kebijakan tambahan seperti Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian.
Tapi dalam praktiknya, hukum yang ada seringkali dianggap multitafsir. Tidak jarang, pasal-pasal tersebut digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang justru sedang menyampaikan kritik. Akibatnya, masyarakat jadi takut untuk berpendapat dan merasa dibungkam. Ini yang disebut dengan efek “chilling effect” dalam kebebasan berekspresi. Hoaks dan ujaran kebencian perlu lebih serius. Dan untuk menekan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan:
1. Revisi UU ITE agar lebih jelas dalam mendefinisikan ujaran kebencian dan tidak mudah disalahgunakan.
-https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang
-tahun-2024?utm_source
-https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/berapa-banyak-orang-indonesia-yang-mamp
u-mengenali-hoaks
2. Peningkatan literasi digital di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar.
3. Peran aktif media sosial dan platform digital untuk lebih cepat menindak konten berbahaya dan membatasi algoritma yang menyebarkan konten provokatif.
Di zaman yang serba digital ini, kecepatan informasi sangat luar biasa. Tapi jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab, informasi itu bisa berubah menjadi senjata yang merusak. Sebagai mahasiswa hukum, kita punya peran penting untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan bijak dalam menangani kasus hoaks dan ujaran kebencian. Hukum bukan hanya alat untuk menghukum, tapi juga untuk mendidik dan menjaga kedamaian masyarakat.
VB-Putra Trisna.